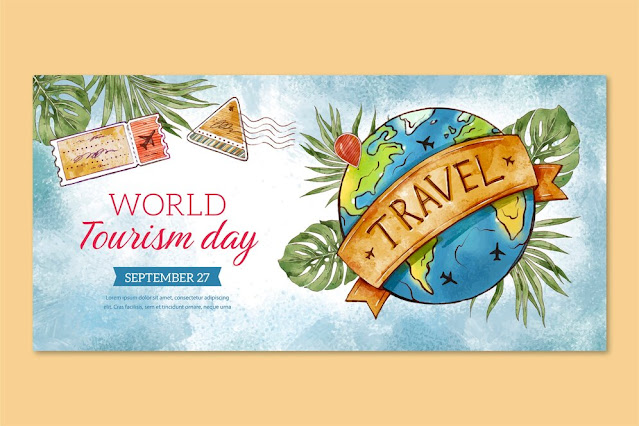(Di-update 2025) Bicara
soal wisata, Surabaya bukan termasuk pilihan pertama untuk wisata alam. Kota-kota
sekitarnya macam Malang atau Mojokerto alamnya jauh lebih bagus. Maka ketika
dengar ada kebun raya di Surabaya, saya sempat mengernyitkan kening. ‘Surabaya
sebelah mana yang tanahnya cukup luas buat dijadikan kebun raya?’
Usut punya usut,
ternyata ini bukan kebun raya biasa tapi kebun raya mangrove. Artinya lahan
hijau ini berlokasi di tepian pantai yang banyak ditumbuhi pohon mangrove. Oh,
masuk akal kalau gitu, sebab Kota Pahlawan ini memang sudah lama punya hutan
mangrove seperti Mangrove Wonorejo atau Mangrove Gunung Anyar. Tempat terakhirlah
yang kemudian dijadikan Kebun Raya Mangrove Surabaya. Jadi memang bukan tempat
yang 100% baru, tapi dinaikkan statusnya (dari hutan biasa jadi kebun raya) dan
ditambah fasilitasnya.
Kebun Raya Mangrove
Surabaya baru dibuka akhir Juli 2023 ini. Mungkin lebih tepatnya re-opening kali,
ya, sebab sebelumnya tempat ini sudah ada dan dibuka untuk umum ketika masih
jadi hutan/wisata mangrove biasa.
Rute
& Transport
Mangrove Gunung Anyar
letaknya di ujung timur Surabaya. Rute ke sini gampang banget. Kalau
dari Raya A. Yani, tinggal lurus terus ke timur aja tanpa belok-belok. Cuma
kalau pakai transportasi umum mungkin agak effort karena jalannya agak
masuk. Kalau naik bemo/mikrolet kayaknya harus jalan lagi agak jauh. Soalnya waktu
ke sana kemarin hanya ketemu bemo di jalan yang masih ramai. Dan itu jaraknya
satu kiloan dari pintu masuk kebun raya. Kayaknya pilihan paling fleksibel ya bawa
kendaraan sendiri atau pesan ojek online.
(Update 2025) Transpor umum:
Saat pergi ke sana lagi,
sempat ngelihat feeder Wira-Wiri (semacam angkot) sampai lokasi. Jadi
sekarang udah bisa pergi ke Mangrove Gununganyar pakai transpor umum.
Jangan lupa pakai
masker dan semacamnya. Hutan mangrove memang adem dan penuh pohon, tapi jalan
ke sananya agak berdebu. Mungkin karena kemarin saya main ke sana saat kemarau,
plus saat siang ketika matahari terik banget, plus pembangunan fasumnya masih baru
thus masih ada material sisa, sehingga banyak debu dan pasir beterbangan
sepanjang jalan mendekati lokasi.
Debu, panas,
pasir-pasir kuning lembut beterbangan di antara roda motor. Vibes musim
kemarau banget, deh.
💡 Tips: Waktu Terbaik
Mengunjungi Kebun Raya Mangrove Gunung Anyar
Berdasarkan
ulasan di GMaps, pagi adalah waktu terbaik. Suasana masih adem, nggak
terik, dan perjalanan ke lokasi pun nggak kepasanan. Dipakai jogging pun
enak. Pilihan kedua adalah sore hari, tapi berisiko kurang santai dan
berkejaran dengan waktu tutup.
Kalau buat selain jogging
alias santai-santai aja, hari terbaik—seperti biasa—adalah hari kerja
karena lebih sepi. Lebih mudah dapat foto tanpa banyak orang lain dan santai
milih duduk di gazebo mana pun.
Kenapa kami milih ke
sini siang-siang, padahal tempat ini pagi pun sudah buka?
Kami berangkat jam 9-10-an
di hari kerja, sampai lokasi sekitar 45 menit kemudian. Alasannya karena waktu
itu ada keperluan dulu aja, sih. Dan kalau berangkat pagi, pertimbangannya
adalah jalanan bakal penuh orang yang berangkat sekolah atau kerja. Jadi milih
agak siangan meski kepanasan di jalan.
Tiket dan Parkir
Untungnya, di lokasi
nggak kepanasan. Dari jalan umum ke titik parkir, ada banyak pohon Casuarina
(cemara laut) yang hijau dan rimbun di kanan-kiri. Aroma khas air laut yang
asin sudah tercium dari sini. Setelah beberapa ratus meter dan melewati rusun
Gunung Anyar, sampailah kami di tempat parkir yang nampak baru dan kering. Di
selatan tempat parkir tampak gundukan yang awalnya saya kira sedang ada
pembangunan. Setelah ngelihat lebih teliti, ternyata itu adalah TPA/Tempat
Pembuangan Akhir.
Jarak tempat parkir
mobil/motor ke gerbang masuk dekat banget. Sekitar 30 meter. Setelah diberi
karcis parkir (Rp5.000,00/motor, mobil Rp10.000,00 kalau nggak salah), kami pun
berjalan ke arah kanan dan masuk ke gerbang.
Berapa harga karcis
masuk Kebun Raya Mangrove? Kurang tahu. Waktu itu kami langsung disuruh masuk
tanpa bayar karena masih dalam rangka reopening.
Harga karcis (update
2025): Rp5.000,00/orang
Di loket masuk juga
bisa milih wahana apa aja yang ingin dinaiki (karena bayarnya sekalian di sini,
bukan di titik wahana). Ada ATV, sepeda air, perahu, dan (semacam) golf
cart.
Seperti layaknya hutan
dan kebun raya, Mangrove Gunung Anyar ini juga sejuk meski letaknya nggak jauh
dari bibir pantai. Kesejukan itu sudah dirasakan sejak sebelum gerbang.
Pohon-pohon cemara laut dan mangrove yang rimbun membuat suasana siang Surabaya
yang terkenal sumuk pol (baca: panas sekaliii) menjadi lumayan adem.
Di Dalam Kebun Raya
Dari gerbang masuk,
rute jalan-jalan bisa dimulai dengan belok kanan ke arah hutan/jogging
track kayu. Sebelum itu, di kanan track ada toko merchandise.
Pengelola juga memajang peta lokasi lengkap dengan track dan spot-spot
seperti gazebo, mushalla, toilet, dan menara pandang. Peta ini dibentangkan
di dekat pintu masuk ke hutan.
Mushalla dan toilet
terletak dekat pintu masuk. Ada satu lagi toilet yang letaknya dekat hutan
cemara. Sementara itu, gazebo tersebar di sekitar jogging track dan
hutan cemara laut.
Selain peta, pengelola
membentangkan banner dengan jenis-jenis tumbuhan yang bisa dilihat
pengunjung di area mangrove. Uniknya adalah yang ditampilkan nggak cuma nama
dan foto bentuk tumbuhannya, tapi juga manfaatnya.
Takjub aja
gitu. Dari banyak pohon dan semak pinggir jalan yang kayaknya “gitu aja”,
ternyata manfaatnya banyak: untuk obat, pengusir nyamuk, makanan atau snack.
Amazed juga karena nama lokal beberapa tumbuhan ini unik banget, bahkan
ada yang jadi nama daerah. Contohnya:
- bogem (=pukul), nama lokal pohon Sonneratia
caseolaris
- bintaro (nama daerah di Jakarta), nama lain pohon Cerbera
manghas
- gedangan (nama daerah di Sidoarjo, kota sebelah
Surabaya), nama lokal Aegiceras corniculatum
Jadi ingat waktu pergi
ke Mangrove Wonorejo. Di sana ada warung yang jual berbotol-botol sirup dari
buah pidada (salah satu jenis mangrove). Rasanya kayak gimana? Sayang saya
belum coba. Waktu ke Gunung Anyar ini pun alpa mengunjungi galeri oleh-olehnya
karena udah kecapekan keliling.
 |
| Buah pidada (Sonneratia caseolaris) alias buah bogem/mangrove apple |
Kami masuk ke kawasan
hutan, yang ada jogging track kayunya. Gapura kayunya memberi kesan
alami meski jelas divernis mengilap. Marka arah jalan, baik yang sekadar dicat
di track maupun yang jadi plang, berwarna cerah mencolok.
Kami pun berjalan di
antara pohon-pohon mangrove. Rimbun. Hijau. Panasnya Surabaya jadi terasa berkurang.
Benarlah kalau pengin suasana adem, tanam pohon relatif lebih efektif daripada
bikin naungan dari material.
Awal-awal, semua masih
hijau. Kita bisa menjangkau daun yang tumbuh dekat ke pagar pembatas. Namun
kalau diperhatikan, ada sela/gap di pohon-pohon. Gap itu
menunjukkan tanah berlumpur di bawah jembatan kayu berwarna abu-abu dan basah,
khas tanah rawa pinggir pantai yang sering tergenang.
Di jalur awal, jogging
track ini masih ada pagarnya. Namun pengunjung harus hati-hati melangkah
ketika sudah agak masuk, terutama yang bawa anak kecil, karena udah nggak ada
pagar pembatas. Makin masuk juga makin banyak nyamuknya. Tips: pakai pakaian
panjang atau pakai lotion anti-nyamuk.
Pada kunjungan kedua
yang bertepatan dengan di musim hujan, tanah rawa itu tergenang agak tinggi.
Sempat ngelihat ada ular kecil menggelesar di perairan. Namanya juga hutan,
wajar kalau banyak hewan liarnya.
Makin dalam, jalur jogging
track ini bercabang-cabang. Untung tadi udah sempat foto peta yang di
depan, jadi bisa buat pertimbangan mau ngarah ke yang mana.
Update 2025: udah ada beberapa
gazebo kayu di area jogging track. Lumayan bisa buat istirahat pas capek
meski kata beberapa teman harus hati-hati karena kadang ada ulatnya.
Yang menarik, beberapa
pohon di sini digantungi semacam kartu nama. Kartu nama ini berisi nama latin
pohon. Ini salah satu poin yang saya suka karena pengunjung jadi tahu jenis
pohonnya dan ngeh bahwa meski semua pohon kelihatan sama, mereka sesungguhnya
beda jenis. Mungkin mereka diberi kartu karena fungsi kebun raya juga sebagai
sarana pendidikan, bukan hanya tempat rekreasi atau healing aja.
💡 Funfact!
Ternyata mangrove ≠
bakau.
Mangrove = kawasan
hutan tepi laut. Jadi tumbuhannya macam-macam, mulai dari pohon sampai semak.
Bakau = salah satu
jenis pohon mangrove, biasanya dari jenis (genus) Rhizospora.
Pendeknya, bakau
termasuk mangrove; tapi mangrove nggak cuma terdiri atas bakau aja.
Galeri Pembibitan
Karena kebun raya juga
punya fungsi edukasi, nggak heran kalau di sini ada beberapa fasilitas itu. Di
dekat gerbang tadi di dekat mushala, ada sebuah galeri pembibitan. Bangunan
serupa ruangan terbuka itu seukuran kamar. Di tengahnya ada instalasi dengan
pipa-pipa dan pucuk-pucuk tunas pohon yang mencuat.
Saya nangkepnya ini
mungkin buat nunjukin tahap pertumbuhan bibit pohon? Karena makin ke kanan
batangnya makin tinggi/makin banyak daunnya. Mungkin kalau sudah cukup
umur/tinggi, barulah dipindah ditanam ke tanah. Sayang waktu itu sedang nggak
ada petugas buat ditanya-tanya.
Selain galeri
pembibitan, di sebelahnya juga ada bangunan terbuka yang dijadikan semacam pojok
baca. Bangunan yang cukup luas ini memiliki tempat duduk dan beberapa rak
buku. Penasaran, saya lihat bukunya. Saya kira isinya bakal tentang
mangrove/bakau/pantai dan semacamnya. Ternyata enggak; bukunya macam-macam.
Nggak bertema, malah.
Dari majalah sampai
buku panduan, ada. Dari buku lawas banget sampai yang terbit lima tahunan lalu,
ada. Saya pengin nyari buku tentang mangrove atau tentang kebun raya mangrove
itu sendiri. Biasanya kebun raya dan semacamnya kan bikin/nerbitin buku macam
begitu. Tapi nggak nemu. Entah memang nggak ada atau saya yang kurang teliti
nyarinya.
Oh ya, di sini juga
ditempel poster hewan-hewan yang bisa ditemukan di kebun raya mengrove
ini. Salah satu yang paling nggak terlupakan adalah kepiting pemanjat pohon
alias tree-climbing crab. Dinamakan begitu karena mereka emang
suka nangkring di pohon. Nggak tinggi-tinggi, sih. Manjatnya juga nggak sampai
sedengkul orang dewasa. Tapi jumlahnya itu lho, banyak banget!
Hewan di Hutan
Mangrove
Selain pohon-pohonan,
namanya hutan tentu ada hewannya. Nah, di sini hewan yang paling sering saya
lihat salah satunya adalah kepiting panjat tadi.
 |
| Kepiting panjat |
Sejak di dekat pintu
masuk, itu kepiting udah kelihatan bertengger di akar-akar napas yang mencuat
ke permukaan air. Ada kali dua puluhan ekor, mungkin lebih? Gerombolan ini
bakal buru-buru sembunyi ke dalam air kalau ada orang lewat.
Makhluk satu ini
rupanya sensitif sama suara. Bahkan waktu kami ngedekatin diam-diam,
pelan-pelaaan banget, mereka bisa langsung lari begitu ini sandal nggak sengaja
nginjak ranting kecil. Ngerasa beruntung kemarin ke sana waktu sepi. Kalau
waktu ramai, apa mungkin kami bisa ngelihat kepiting sebanyak ini? Saya sendiri
bisa ngelihat kepiting sebanyak itu kalau di pasar aja, hahaha.
Selain kepiting, yang
bikin berkesan adalah burung-burung di sana. Nggak kelihatan, sih, burungnya
apa. Saya nggak tahu jenisnya apa aja. Yang saya tahu, suara burungnya
beda-beda. Ngedenger suara banyak burung di dalam hutan yang semilir, berasa
adem, damai, dan… nggak percaya. Ini masih di Surabaya yang rame dan sumpek banget
itu, ya?
Aviary! (updated
2025)
Di tengah hutan/jogging
track ada aviary atau kandang burung sekarang. Bentuknya seperti
kubah atau dome. Dari agak jauh udah kelihatan.
 |
| Aviary Mangrove Gununganyar |
Bentuknya yang seperti
setengah bola dari jaring. Sekilas mengingatkan saya pada dome serupa di
film dinosaurus Jurassic Park.
“Untung nggak ada dinosaurusnya.”
“Lha kan burung itu
masih keturunan dinosaurus.”
“Oh, iya juga, ya.”
— sepenggal percakapan
kami di lokasi
Seorang teman yang
tahu kami main ke mangrove, sempat berkomentar, “Nggak kena ulat di area
serimbun itu?”
Alhamdulillah enggak,
sih. Dia cerita kalau dulu di lokasi yang sama pernah nemu ulat banyak. Kali
ini, entah: saya yang kurang memperhatikan, atau bukan musim ulat, atau kontrol
hamanya bagus, jadi saya nggak menemukan ulat yang katanya gatal itu. Syukurlah.
Hutan Cemara
Lanjut ke jalan-jalan.
Apa pemandangannya cuma bakau/mangrove? Enggak, dong. Ada juga tempat yang khas
pantai banget: hutan cemara. Hutan cemara ini terletak setelah jogging track.
Jangan bayangin cemara
di sini seperti cemara-cemara beraroma pinus segar seperti di pegunungan.
Enggak, cemaranya beda. Cemara di tepi laut biasanya adalah cemara laut/cemara
udang (Casuarina equisetifolia).
Pernah dengar Pantai
Gua Cemara yang ada di selatan Yogya? Di sini area cemaranya memang nggak
seluas Pantai Gua Cemara, tapi kita tetap bisa menemukan pemandangan yang
mirip: dahan-dahan cemara yang bertautan membentuk kanopi alami yang melengkung
menaungi kita dari panas pesisir.
Di area inilah
terdapat beberapa gazebo dan tempat duduk di sepanjang jalan. Nggak banyak,
tapi cukup. Ada toilet juga. Lumayan membantu karena jarak dengan toilet
pertama cukup jauh (toilet ada di dekat gerbang).
Di ujung jalan ‘gua
cemara’ ini terdapat menara pandang. Menara berkapasitas maksimal 10 orang ini
bisa dinaiki untuk melihat ekosistem mangrove dari atas. Memang nggak tinggi
banget, pun nggak sampai kelihatan laut, tapi cukuplah. Bila cerah, pegunungan nun
jauh di Kab. Malang bisa kelihatan mengintip dari balik rimbun hutan mangrove.
“Harusnya kita bawa
makanan, ya, biar bisa piknik,” ujar partner jalan saat itu.
“Atau bawa buku. Cozy
banget kayaknya duduk-duduk bawah gazebo sambil baca,” saya menanggapi.
Maka di kesempatan
selanjutnya, kami pun bawa sedikit jajan dan air minum. Namun saat itu kami
nggak piknik karena aroma guano (kotoran burung) yang menyengat.
Keluar dari hutan cemaran dan kembali ke arah gerbang masuk, di sebelah kanan ada sungai dengan perahu yang siap mengantarkan wisatawan menyusuri perairan. Waktu itu di sebelah kanan ada bagian yang sedang dalam pembangunan, entah apa. Sementara di sebelah kiri ada Science Centre dan kantin. Penasaran sama kuliner Surabaya? Bisa sekalian coba menu rujak cingur di sini.