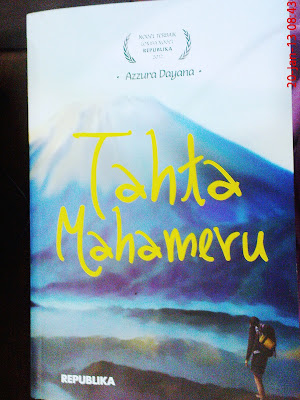April 24, 2013
BY Hijau Biru
2 Comments
“Masnya anak IPA? Waah, ya sudah, Mas. Pasti sudah terjaminlah hidupnya.”
dan
“Kamu masuk IPA atau
IPS?”
“Alhamdulillah, IPA.”
Ckiiiit!
Why? Why? Mengapa? Mengapa semudah itu masyarakat kita melebihkan
derajat ilmu alam dan menjelentrehkan martabat ilmu sosial? Saya anak IPA, suka IPA, memilih masuk IPA, tapi ikut cekit-cekit gitu rasanya kalo ada yang bilang IPS itu kurang penting.
Mayoritas beralasan
bahwa sainslah yang mengubah keadaan dunia satu abad ini. Penemuan penicillin,
pasteurisasi, relativitas, hingga bom atom yang mengubah jalan cerita Perang
Dunia II semuanya sama-sama berhubungan dengan ketiga pelajaran yang sudah
menjadi ciri-ciri anak IPA: Biologi, Fisika, dan Kimia. Ya, semua itu memang
betul. Memang ilmu alam sudah mengubah dunia dalam beberapa ratus tahun
terakhir ini.
Namun, bukannya ilmu
sosial juga berdampak sedemikian jauh? Perang dunia dimulai dengan perebutan
daerah pemasaran pasca revolusi industri. Negara-negara Barat berlomba-lomba
mengklaim negara X di Asia adalah daerah pemasarannya. Kenapa saya merasa ada
unsur ilmu Ekonomi ya di sini? Dan saat
perang dingin AS-Rusia, bukankah mereka berbeda pendapat tentang ideologi? Dan,
hei, itu ilmu sosial juga, bukan?
Ah, itu kan, cuma
sebagian kecil contoh ilmu sosial yang berguna. Sisanya? Guna nggak?
Oke. Sebuah contoh:
(amat)(sangat) banyak (sekali) siswa lulusan SMA di Indonesia yang menginginkan
tembus menjadi mahasiswa FTTM a.k.a pertambangan di ITB. Lho, itu kan Fisika?
Tapi tahu darimana ada wilayah pertambangan di Indonesia kalau nggak baca di
buku paket IPS zaman SD? Dan kalau ilmu
sosial memang dipandang sebelah mata, kenapa situ orang banyak yang ambil
jurusan Ekonomi, Akuntansi, maupun Hubungan Internasional?
Meskipun begitu, tetap
saja. Orang Indonesia sudah sejak dulu di-mindset-kan
IPA. Sejak zaman Belanda, malah. Sudah
pada dengar kan soal STOVIA (sekolah kedokteran Belanda)?
Seorang teman yang
penasaran, mengacungkan tangan pada saat pelajaran Sejarah.
“Kenapa orang Indonesia ber-mindset IPA itu pasti bagus ya, Pak?
Kan, tanpa IPS, negara juga nggak bisa jalan.”
Benar juga. Mayoritas
roda pemerintahan dijalankan oleh ilmu IPS. Tata Kewarganegaraan, Ekonomi,
Sosiologi. IPA?
“Ya memang begitu, Nak.
Orang kita memang sudah dibentuk pikirannya oleh Belanda kalau ilmu sains itu
lebih penting dari ilmu sosial.”
“Kenapa, Pak? Padahal
kalau saya perhatikan, di luar negeri banyak juga yang kuliah di ilmu sosial.”
“Waaah, kalau orang
Indonesia belajar ilmu sosial bisa bahaya, Nak! Kalau orang kita belajar
geografi, mereka bakal tahu tempat-tempat penambangan strategis, letak-letak
sumber daya Indonesia yang amat sangat melimpah. Nah, kalau orang Indonesia
waktu itu diajari Sejarah? Bahaya juga! Semangat kita bisa langsung membara
begitu tahu nenek moyang kita dari Majapahit dan Sriwijaya hampir menguasai
Asia Tenggara. Bahaya, Nak! Makanya kita di-mindset-kan
IPA, supaya orang Indonesia nggak tahu seberapa kuat kita sebenarnya. Kalau
kita tahu? Wah, Belanda bisa ajur dari dulu, Nak!
“Oleh karena itu, kita
dibentuk jadi orang IPA. Orang Barat pintar, Nak, di negara mereka sendiri,
ilmu sosial juga digalakkan, nggak IPA aja. Kenapa? Ya supaya nggak jadi kayak
kita!”
Ah, jadi apa yang
terjadi sekarang ini sudah diwariskan Belanda sejak dulu. Agar kita menjauhi
ilmu sosial, agar negara asing bisa mengeruk kekayaan kita, bisa tetap
‘menjajah’ Indonesia meskipun statusnya sudah merdeka de facto dan de jure.
Lagipula, akui sajalah,
meskipun orang kita mendewakan ilmu alam, benarkah kita benar-benar
menjunjungnya? Adakah ilmuwan Indonesia yang didanai demi risetnya? Kabar
paling santer yang saya dengar, seorang insinyur lulusan Jerman bahkan harus
menelan mimpinya untuk membuat pesawat buatan anak negeri, karena pabrik pesawatnya
ditutup (dan akhir-akhir ini kabarnya membuka pabrik sendiri). Paling pol, ada
sekelompok ilmuwan barat yang blusukan ke Kalimantan atau Papua dan menemukan
spesies baru tumbuhan.
Bukannya orang Indonesia
nggak ada yang benar-benar menggeluti ilmu sains sampai notok jedhok, dengan serius. Buktinya, orang-orang macam ini(posting menyusul)
masih ada.
Banyak orang Indonesia
yang menguasai ilmu alam. Sungguh banyak. Namun, tak semua mau
mengksplorasinya. Tak semua mau memelajarinya dalam-dalam dan membuat suatu
penemuan baru. Orang masuk ilmu alam rata-rata karena satu alasan: supaya aman.
Yang anak SMA, masuk IPA supaya nanti bisa enak milih jurusan di universitas (ada
jurusan yang anak IPA bisa masuk jurusan anak IPS, namun tak berlaku sebaliknya)
dan nggak dicap bodoh. Yang sudah kuliah, demi prestise. Intinya satu: keamanan
status sosial (nah lho, balik deh ke Sosiologi).
Karena alasan ‘keamanan
status sosial’ inilah, teman saya pernah sinis (sebut saja K) ketika tahu ada
teman Z yang ingin menjadi dokter.
K: “Kamu nanti mau
kuliah jurusan apa?”
Z: “Kedokteran.”
K: (Tersenyum sinis)
“Kenapa? Pengen kaya?”
Memang ironis bahwa
kebanyakan siswa memilih Fakultas Kedokteran sebagai pelarian agar bisa kaya
secara instan. Tapi, hei, jadi dokter bukan jaminan jadi kaya, kok. Kakak kelas
saya ada yang jebolan kedokteran dan malah jadi pemusik (dan sukses). Ada juga
yang banting setir jadi pedagang. Tetangga saya dokter dan awal-awal dia jadi
dokter dulu, bisa dibilang kisahnya tak semanis yang dibayangkan. Ditempatkan
di kota terpencil dengan keterbatasan alat-alat kedokteran, belum penyakit
tropis yang seabreg, dan gaji yang tidak pernah dibayangkan.
Jadi, jangan heran jika
sekarang marak kasus malpraktik. Karena motivasi menjadi dokter bukan lagi
menolong orang, tapi supaya bisa hidup enak.
Jadddiiiii, IPA itu
jelek? Gitu?
Nggak. Ilmu alam itu
sepenting ilmu sosial dan Ilmu sosial itu sepenting ilmu alam, saling
melengkapi. Nggak ada dua-duanya, nggak imbang. Mana bisa pemerintahan jalan
kalau cuma dijejali penemuan? Mana bisa penemuan berjalan kalau nggak ada
dukungan pemerintahan?
Enak aja ngomong. Lu kan
nggak ngerasain jadi kita-kita yang hidup di bawah standar gara-gara keprosok
ke ilmu sosial!
Saya menyadari bahwa di
Indonesia ini hidup dari ilmu sosial tidak semudah hidup dengan ilmu alam, seperti
kata ayah saya (“Apa? Kamu mau masuk jurusan Sejarah? Mau jadi apa kamu? Kerja
ngelap patung di museum?”). Tapi kalau begini terus, ya kapan majunya? Kapan
bikin perubahannya? Harus ada yang berkorban, itu pasti. Dan pasti ada yang mau
berkorban, entah satu orang, dua orang, segelintir, dua gelintir. Hasilnya
memang belum terlihat. Tapi kalau mau yakin dan kerja keras, apa sih yang
nggak?
Yakin dan kerja keras,
itu salah satu hal yang ditanamkan kakak kelas (dan semoga dilanjutkan ke
generasi-generasi selanjutnya) selama belajar berorganisasi. Yakin dan kerja
keras, itu yang akan membuat perubahan. Semenanjung Arab tidak masuk Islam pada
satu malam, seperti Amerika Serikat tidak menjadi negara adidaya karena perang
satu hari.
Jadi, IPA-IPS, sekarang
damai ya? V^o^V
---
Tambahan:
Karena agak sentimen sama ilmu sosial ini juga lah, yang bikin (negara) kita tertinggal di beberapa aspek. Misal? Nggak tahu betul atau enggak, konon katanya ada beberapa sejarah kita yang dimanipulasi oleh bangsa asing biar nggak terlihat 'wah keren banget'. Kenapa bisa gitu? Ya karena sejarawan yang expert dalam sejarah kita justru orang asing. Kebetulan juga, mereka generasi sejarawan pertama yang mengungkap itu. Jadi kalau disitasi, pasti sumber pertamanya beliau. Coba cek aja, di Belanda misalnya, banyak manuskrip dan artefak kita yang justru ada di sana. Jurusan sejarah Indonesia, bahasa Indonesia, dll pun marak di negara tetangga, Australia misalnya.
Seorang teman pernah nyeletuk, "Sebel kalau ada yang bilang kenapa ilmu pengajaran, teori sosial, dll itu kita harus ikut teori Barat. Lha, sendirinya, kalau ada orang yang menekuni ilmu itu di sini, dibilang 'mau jadi apa' kok. Jadi mau ambil ilmu dari mana lagi, karena di kita sendiri nggak didukung, jadi nggak maju, riset sosial kita lemah, dan pada akhirnya buat praktisi harus ambil ilmu dari Barat karena mereka emang lebih mumpuni?"