Ketika sudah ‘lumayan akrab’ dengan
perpustakaan online, saya punya hobi baru: ngecek buku yang pengin
dibeli. Bukan apa, tapi akhir-akhir ini saya tergolong sering nemu buku yang review-nya
menarik atau selangit, tapi begitu udah beli dan baca, eh, ternyata nggak
sebagus itu atau nggak sesuai selera saya.
Jadi untuk jaga-jaga, biasanya
selain tanya pendapat teman yang udah baca, saya coba baca preview-nya
di perpustakaan online macam iPusnas (btw ini gratis, akses gampang,
perpus milik perpus nasional). Kalau belum tersedia di sana, saya baca lewat
Google Books. Kalau intronya atau bab-bab awal terasa menarik, gaslah ke toko
buku.
___________________________
Anw sebelum terlalu panjang karena postingan ini campur curhatan pribadi,
yang cari review bisa lompat ke bagian ini (klik):
___________________________
Sama kayak buku “Save The Cat” ini. Buku
tulisan Jessica Brody ini menulis tentang teknik menulis sebuah novel yang
menarik, memikat, mengikat, yang diberi nama teknik ‘Save The Cat’. Buku ini
udah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia tahun 2021 lalu. Dan karena di-endorse
(dan udah dipraktikkan) oleh salah satu penulis favorit saya, maka saya
jadi tertarik beli, ahahah.
Tapi...
... sebenarnya saya kurang suka ngulik
metode nulis begini. Saya lebih suka nulis tanpa bikin struktur rinci,
rancangannya cukup di kepala atau garis besar aja (kecuali waktu nulis non-fiksi atau tulisan
yang agak panjang). Namun karena Dewi Lestari bilang bahwa ngertiin struktur
bisa banget dipakai untuk ngatasi writer’s block dan cerita yang mbulet
atau malah stuck (yang mana adalah masalah saya selama bertahun-tahun,
huhu), jadi tertarik, deh.
Karena ‘khawatir’ kurang cocok inilah, saya
pun cek dulu isinya lewat perpus online. (Apalagi belakangan ini banyak
banget kan buku metode menulis fiksi yang membanjir tapi isinya mirip atau
gitu-gitu aja. Nggak mau rugi, dong. Sayang kalau isinya sama kayak pelajaran
di sekolah dulu atau bisa didapat semudah browsing internet.)
Tujuan pertama adalah Google Books. Seperti
udah diduga, di sana memang ada tapi hanya beberapa bab (namanya juga preview).
Terus terpikir, coba cari di iPusnas, ah. Siapa tahu malah ada versi full-nya?
Dan...
Jeng-jeng! Memang ada. Nggak butuh waktu
lama, saya langsung klik tombol pinjam.
Menelusuri daftar isi, ucapan terima kasih,
kata pengantar... oke.
Tapi, eh, kok kayaknya beda dengan preview
yang pernah saya baca di Google Books? Nggak apa-apalah, lanjut aja. Baru
ketika bab 1 udah kelar, saya bandingin sama yang di G-Books. Eh lho, ternyata
emang beda! Yang lagi saya baca adalah Save The Cat untuk skenario film besutan
Blake Snyder, sedangkan versi novel yang (rencananya) pengin saya beli adalah
tulisan Jessica Brody. Pantesan aja rasanya ada yang beda, karena seingat saya
pengantarnya ditulis Dee Lestari, sedangkan yang sedang saya baca, ditulis Gina
S. Noer (pembuat film).
Mengapa buku Save The Cat ada dua?
Bukan ada dua, sebenarnya. Tekniknya cuma
satu. Hanya aja buku yang satu soal penyusunan skenario, satunya spesifik
tentang menulis novel. Seenggaknya itu yang versi (terjemahan) Indonesia.
Mana yang ‘betulan’?
Dua-duanya betulan. Save The Cat-novel
merupakan pemekaran dari Save The Cat-skenario.
Jadi ceritanya, metode Save The Cat
(disingkat jadi STC aja yak) pertama digagas oleh Blake Snyder untuk penulisan
skenario. Lalu murid Snyder, Jessica Brody, mempraktikkan ini dalam prosesnya
nulis novel. And it worked! Jadilah Brody nyusun buku tentang STC untuk
penulisan novel.
Dan karena saya memang sukanya nulis buku
dan bukan skenario, maka sebenarnya yang pengin saya baca aslinya adalah buku
susunan Brody.
Tapi... STC-novel ini nggak tersedia di
iPusnas. Yang ada ya STC-skenario sehingga ini yang bisa dibaca lengkap. Nggak
papalah, saya pikir. Kan STC-novel ‘akarnya’ dari STC-skenario ini. Pasti
ada hal yang bisa diambil buat penulisan novel meski mungkin butuh penyesuaian.
Let’s go!
Review Save The Cat – Blake Snyder
Sebelum baca bukunya, saya udah pernah cari
info soal metode STC ini. Sekilas intinya kayak nempel poin-poin penting sebuah
cerita dan diurutkan. Kalau lihat papan tempelannya, kelihatan penuh post-it.
Memang, poin-poin di STC ini ada sampai 40. ‘Banyak banget,’ batin saya
yang waktu itu lalu ‘meninggalkan’ STC karena ngerasa ribet.
Intinya, metode STC membagi kejadian dalam
beberapa babak/poin tadi. Total ada 15 babak. Banyak? Iya. Namun kalau
ditelusuri lebih dekat, 15 babak ini sebenarnya perincian dari 3-4 babak utama
aja. Pernah dengar struktur 3 babak? Ini struktur umum yang isinya intro –
tengah/konflik – penutup/resolusi/ending. Nah, STC merinci 3 babak ini
lebih detail. Kenapa? Karena, kalau saya, nulis panjang
‘cuma’ pakai 3 babak ini masih bikin bingung ‘mau dibawa ke mana’ karena
terlalu umum.
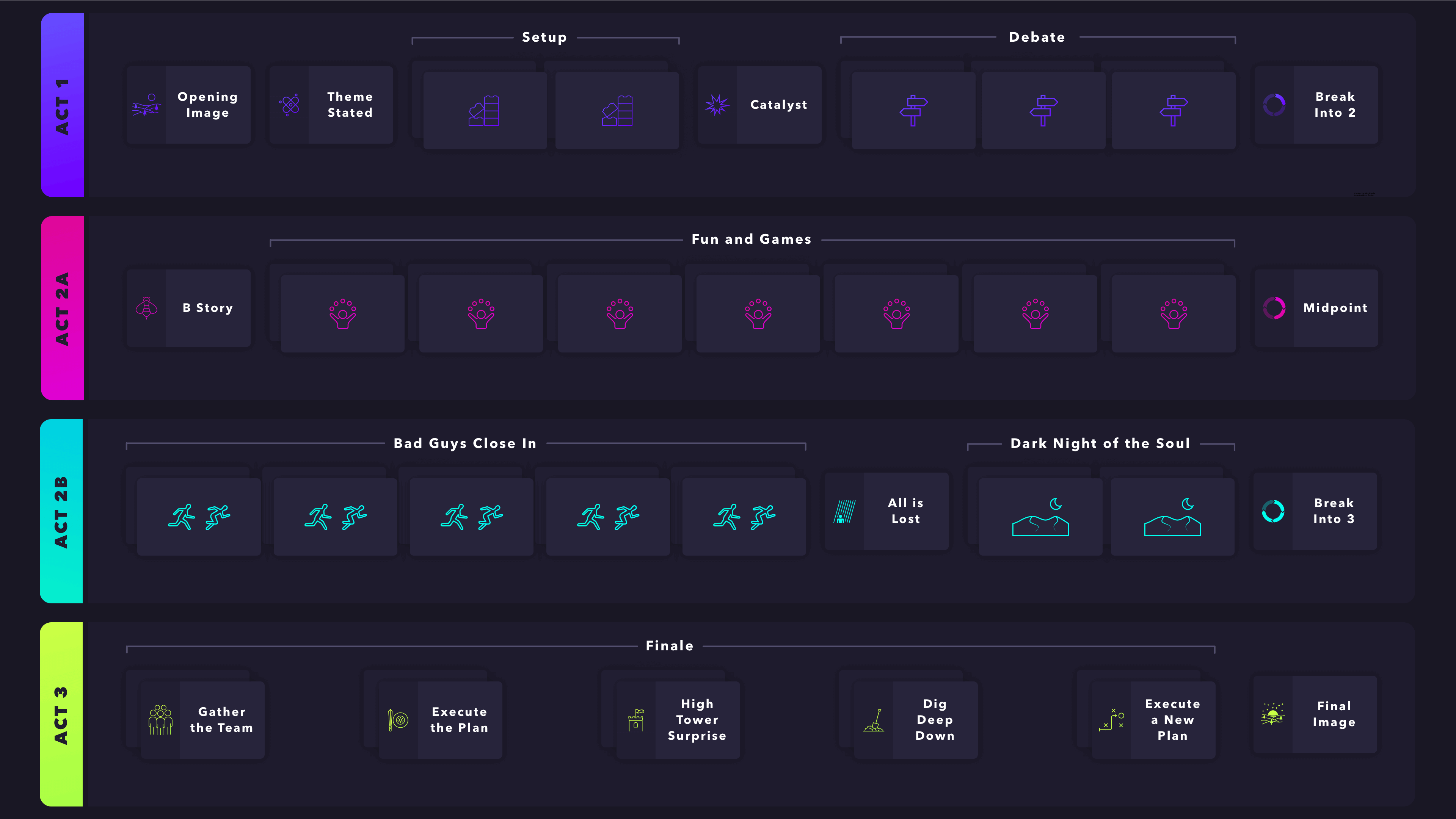 |
| Papan Save The Cat dari studiobinder.com |
Jadi STC ini merupakan rincian dari 3 babak itu.
Btw grafik STC ini macam-macam. Makanya kalau browsing, kita akan ketemu beberapa versi. Tapi nggak usah bingung, intinya tetap sama di 15 beats itu. Bedanya cuma di peletakan di grafik aja.
STC-skenario menjelaskan 15 babak ini diisi
apa aja. Sebuah pencerahan buat saya, karena grafik naik-turun konflik dan
emosi dijelaskan rinci di sini: apa yang terjadi, gimana pergolakannya, dsb.
Nah, dalam masing-masing babak ini diisi 2-4 kartu yang isinya
peristiwa-peristiwa yang ingin kita masukkan dalam cerita. Kebanyakan sampai
totalnya lebih dari 40? Nggak apa-apa, nanti bisa diseleksi. 40 poin/kartu ini
kemudian disusun dan dirajut sedemikian rupa, detailnya di buku.
Adegan/peristiwa paling ujung dalam sebuah
babak harus merupakan penyambung atau lontaran untuk masuk ke babak
selanjutnya. Waktu baca ini, sekilas saya jadi ingat metode nulis yang dibilang
Pak Gol A Gong dan A.S. Laksana. Keduanya juga menyatakan hal yang sama. Jadi
ingat pula soal kohesi-koherensi kalimat.
Selain tentang rincian babak (atau yang di
STC sering disebut beat sheet), buku ini juga punya penggolongan cerita.
Pengkategorian di sini nggak sekadar genre romance, thriller, dsb, tapi lebih
spesifik. Sebuah cerita cinta-cintaan dan sebuah film pencarian jati diri bisa
aja termasuk ‘genre’ yang sama karena punya plot yang mirip. Oleh karena itu,
banyak yang nyebut penggolongan ini sebagai ‘plotting genre’.
Kalau pernah dengar tipe plot macam Cinderella’s
story, rags-to-riches, dsb, rasa-rasanya plotting genre yang dibahas
di STC mirip dengan itu. Bedanya di STC ada 10 genre: mulai dari Golden Fleece sampai
Monster In The House. Genre ini bisa ngebantu kita nentuin mana ‘perjalanan
cerita’ yang cocok sama cerita kita.
Selain ngebahas teknik, buku ini juga
ngomongin soal kesalahan yang umum dilakukan. Beberapa mungkin pernah kita
dengar, antara lain:
- dialog bertele-tele,
- Double Mumbo Jumbo, yang berarti kejadian
fantastis yang jumlahnya kebanyakan (kayak yang sering terjadi di sinetron
kita. Ujian ini ditambah peristiwa itu terus ditambah lagi sampai yang nonton overwhelmed)
- Pope In The Pool, yang rasanya mirip tips
nulis yang menggabungkan setting atau latar dengan aksi tokoh supaya
nggak ngebosenin dan terlalu eksposisi (cara ini sering saya pakai kalau nulis travel-writing
atau cerpen yang temanya travelling)
dsb.
Pada intinya, STC ini metode supaya kita
sebagai pembaca/penonton memihak ‘Hero’ alias tokoh utama dalam cerita.
Teknik ini dirinci jadi 15 babak – 40 kartu – pemilihan plotting genre tadi. Buku
ini juga banyak ngebahas soal penokohan, karena poinnya adalah keberpihakan ke
Hero.
Jadi, apa STC-skenario ini bisa dibaca
untuk panduan bikin novel?
Bisa banget. Meski bukunya ngomongin
skenario, tapi tekniknya applicable banget untuk novel.
Gimana dengan media lain, misalnya cerpen
atau artikel?
Ada poin-poin yang tetap bisa banget
dipakai, seperti hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan atau kesalahan
yang umum dilakukan tadi. Namun karena babak/beats-nya banyak, mungkin
soal beats ini aja yang nggak applicable. Bikin cerpen/artikel
dengan 15 beats kayaknya terlalu penuh; pakai struktur 3 babak aja
cukup. Kalau novelet, masih bisalah pakai STC karena rada panjangan.
Setelah tamat dengan STC skenario, sekarang
kita beralih ke...
Tentang “Save The Cat: Writes A Novel” oleh
Jessica Brody
Karena buku ini belum tersedia di iPusnas
dan di G-Books hanya ada preview-nya, maka ini bahasan sesuai halaman
yang bisa saya ‘intip’ di sana.
Dilihat dari daftar isi, STC-novel ini
babnya banyak dipenuhi bahasan tentang plotting genre (itu lho, yang
kayak Golden Fleece atau Rags to Riches tadi). Bedanya dengan STC-skenario, di
sini isinya lebih dirinci dengan elemen-elemen yang harus ada di tiap plotting
genre. Contohnya genre Golden Fleece yang punya elemen cerita berupa jalan
(perjalanan tokoh), tim/teman, dan hadiah.
Kalau browsing di tempat lain,
masing-masing plotting genre punya 3 elemen. Elemen ini ngebantu banget
kalau pengin mempertajam cerita. Misal, kita nulis cerita soal petualangan.
Nah, supaya petualangannya lebih greget dan nggak lempeng, apa aja yang harus
ada dalam cerita? Inilah yang dibahas per elemen.
Selain ada elemennya, STC-novel juga ngasih
contoh rinci banget tentang novel/film di masing-masing genre. Benar-benar
dibedah. Kayaknya ini nih yang bikin bukunya jadi tebal, karena satu novel bisa
dibedah elemen dan beats-nya sampai berlembar-lembar. Di satu sisi, ini
ngebantu banget buat yang nyari contoh supaya bisa lebih paham materi di bab
itu. Di sisi lain, mungkin ada yang ngerasa too much, terlalu detail;
termasuk saya. Bagian ini saya baca sekilas aja karena saya cuma pengin tahu
tentang genre-genre ini secara umum dan pengin langsung aja ke bahasan
selanjutnya.
Perbedaan lain antara buku STC-skenario dan
STC-novel adalah buku STC untuk penulisan novel lebih ramah pemula. Di sini
diterangin dari awal tentang tetek-bengek pembabakan dan penulisan. Di
STC-skenario, bahasannya langsung to the point ke perumusan babak; langsung
ke teknis beat sheet. Pembahasan seperti penokohan, nama babak, dsb, tetap
ada tapi rasanya nggak serinci di STC-novel. Orang yang baru pertama nyemplung di dunia tulis-menulis mungkin akan bingung begitu di lembar-lembar pertama langsung ketemu dengan berbagai istilah seperti midpoint, B-story, dsb. Kalau orang yang udah agak lama nyemplungnya, ini bukan masalah karena udah kenal istilah itu. So, STC-skenario bukunya
lebih to the point.
Jadi untuk yang baru mulai nulis, buku Save
The Cat versi novel (Jessica Brody) lebih recommended. Untuk yang udah beberapa
saat nyemplung di dunia kepenulisan, versi skenario (Blake Snyder) bisa
langsung dilahap. Buku STC versi skenario bisa dibaca gratis secara daring di
aplikasi iPusnas.
Kesan tentang Save The Cat
Sebagai orang yang lebih suka nulis ngalir
aja alias strukturnya ngawang di kepala, awalnya maju-mundur mau baca STC. ‘Toh
udah pernah baca/ikut kelas penulisan lainnya’, pikir saya waktu itu. Namun,
sebuah petuah dari (lagi-lagi) Dee membuat saya tercenung, “Kalau buntu saat
nulis, itu artinya ada yang salah dengan struktur cerita.”
Saya melirik bab-bab tulisan yang
terbengkalai lama sekali. Ya, persis, itu ‘penyakit’ saya: buntu, ngerasa tulisan
kurang greget. Padahal saya udah coba beberapa teknik lain. Cuma, setelah baca
STC, rasanya teknik yang pernah saya pakai itu terlalu umum; kurang detail,
jadilah tulisan jadi lempeng-lempeng aja.
Jadi, apakah STC ini cocok untuk penulis model pantser?
(alias yang suka nulis ngalir tanpa bikin kerangka)
Berkaca dari saya sendiri, rasanya cocok-cocok aja. STC bisa ngebantu saat kita buntu ini cerita mau dibawa ke mana atau saat kehabisan ide dengan ngelihat 40 kartu beat sheet yang berisi momen penting. Toh bikin struktur bukan berarti itu kerangka nggak bisa diubah kalau ada yang dirasa kurang cocok. Ngelihatin list ide juga bisa bikin inspirasi terpantik. Dan, kalau buntu, kita bisa lebih mudah menelusuri bagian yang bikin cerita buntu atau nggak asyik.
Mengutip kata-kata Jessica Brody, yang kurang lebih,
Bagi penulis tipe plotter, STC ibarat peta yang memandu mereka selama perjalanan. Bagi pantser, STC lebih seperti montir yang membantu mereka memperbaiki kendaraan bila dalam perjalanan timbul masalah.
Sejenak setelah menekuri poin-poin STC, reaksi saya, “Wah, padat banget!”
Plotnya padat seperti berkejaran. Setelah kejadian menegangkan A, masuk poin menegangkan B, dst. Sekilas kayak nggak ada jeda untuk bernapas. Namun kalau dipikir-pikir, ya emang ‘feel’ tulisannya jadi lebih dapat; lebih seru. Beberapa novel yang saya tahu dibuat dengan teknik STC pun terasa lebih asyik, page-turner banget, surprise-nya nggak habis-habis (meski kadang berasa ‘ini nggak ada istirahatnya ya?’ tapi tetap seru!).
Mungkin metode ini cocok untuk novel yang isinya padat dan butuh tempo yang cepat (untuk ‘mengikat’ pembaca). Kalau pengin nulis novel yang temponya lebih slow, mungkin bisa dikondisikan dengan utak-atik beat sheet STC atau pakai metode lain.
Apa teknik STC bisa digunakan untuk jenis
tulisan lain?
Hmm, tergantung jenis tulisannya. Untuk
tulisan pendek macam cerpen kayaknya kurang cocok karena beats-nya
banyak, sedangkan ruang untuk cerpen terbatas. STC cocok
untuk konflik yang kompleks berlapis, sedangkan konflik cerpen butuh selapis aja.
Kalau untuk novelet, mungkin masih bisa.
Meski begitu, beberapa poin pembahasan di
buku STC bisa banget dipakai untuk jenis tulisan lain. Contohnya tentang penokohan
(bisa dipakai di cerpen), Pope In The Pool (bisa dipakai di artikel/cerpen/travel-writing),
pentingnya subteks, dsb.
Teknik STC ini udah banyak yang bahas di internet.
Grafiknya bejibun. Ada website-website yang ngebahas rinci bahkan nyediain tools
gratis untuk identifikasi plotting genre tulisan kita (apalagi
website berbahasa Inggris). Cuma kadang infonya terpotong-potong, jadi (kalau
saya) lebih enak baca bukunya karena langsung ada di satu tempat.
Buku STC-novel dan STC-skenario dua-duanya
sama-sama worth the time. Mungkin, inilah solusi yang saya cari selama
ini, hahaha. Setelah ini mau coba ah, semoga cocok dan bisa memecahkan
kebuntuan menahun ini 😄
= = = = =
Selain buku Save The Cat, ada beberapa buku lain tentang metode menulis yang menurut saya gampang dipahami. Gampang banget bahkan untuk yang baru mulai nulis. Buku-buku inilah yang ngebantu saya nulis lebih baik di saat panduan menulis (waktu itu) hanya ada buku panduan formal sedangkan saya nulis teenlit.
Penasaran, nggak? Semoga bisa ditulis di postingan selanjutnya, hehe.


.jpg)

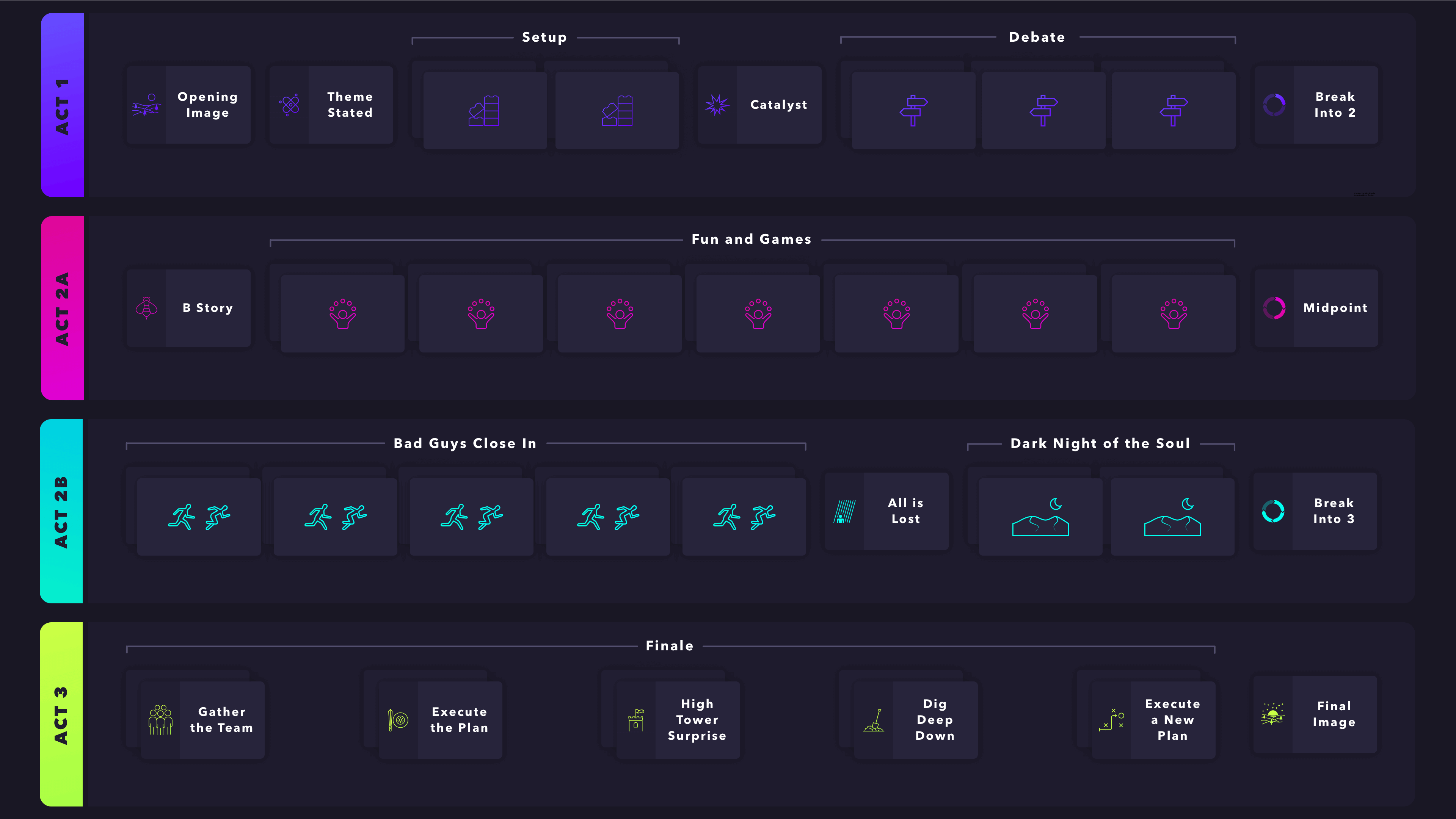

.jpg)


