Seminggu lalu, tepat di 16 Desember, adalah 54 tahun meninggalnya Soe Hok Gie. Aktivis dan pendiri Mapala UI itu meninggal di Gunung Semeru bersama dengan temannya, Idhan Lubis. Hari itu, beberapa poster peringatan hari kematiannya bermunculan di media sosial. Poster-poster itu mengingatkan saya tentang sebuah buku yang pernah saya baca di bulan yang sama, tahun lalu.
Buku itu berjudul “Soe Hok Gie, Sekali Lagi”. Buku yang pertama terbit tahun 2009 inilah yang jadi gerbang untuk saya untuk menemukan buku pendakian zaman (amat) lawas.
“Soe Hok Gie, Sekali Lagi” adalah kumpulan esai tentang Gie dari orang-orang yang dekat dengannya. Ada pula esai dari orang-orang yang tidak pernah ia temui tetapi ikut terlibat dalam pembuatan film “Gie”, antara lain aktor Nicholas Saputra, sutradara Riri Riza, dan produser Mira Lesmana. Dalam buku 500-an halaman itu, ada satu bagian cukup panjang yang ditulis oleh Rudy Badil—yang kemudian menjadi wartawan Kompas—yang ikut dalam pendakian saat itu. Bagian inilah yang menarik perhatian saya.
Tulisan Rudy menceritakan pendakian mereka ke Semeru. Lengkap. Sejak awal persiapan berangkat sampai pengebumian Hok-Gie dan Idhan. Esainya juga menceritakan ingatan-ingatan tentang teknis dan medan pendakian saat itu. Jalur mana yang ditempuh, apa saja yang ditemui, hambatan-perselisihan-dinamika tim yang terjadi di lapangan. Seperti pendaki lain, tim pendakian mereka juga mencari data pegunungan dari catatan perjalanan pendaki-pendaki sebelumnya. Kebetulan yang dijadikan rujukan adalah buku C.W. Wormser, seorang petualang Belanda.
Nama Wormser beberapa kali disebut. Catatan perjalanannya, selain cerita soal gunung dan perjalanan itu sendiri, juga jadi sumber catatan sejarah yang terjadi di sekitar Gunung Semeru di masa lalu. Dari nukilan catper (catatan perjalanan) Wormser inilah saya jadi tahu kalau sejak dulu sudah ada tanah pertanian di Ranu Pani (desa terakhir sebelum hiking ke Semeru), bahkan peternakan sapi. Selain soal Semeru, catatan Wormser juga disebut-sebut memiliki tulisan perjalanannya ke gunung-gunung lain.
[Wormser]
Sebelum Wormser, saya pernah menemukan catatan-catatan dan nama-nama penjelajah/pendaki lain. Antara lain cerita dari Junghuhn, van Bemmelen, dsb. Namun, catper mereka isinya lebih seperti laporan. Deskriptif sekali, “poin-poin banget”, ilmiah pol (kecuali Junghuhn, yang kadang nulisnya ngalir kayak diary). Mau gimana lagi, mereka emang nulis untuk keperluan laporan eksplorasi pemerintah Hindia-Belanda, bukan untuk majalah. Jadi ya emang kaku sekali. Lebih cocok untuk referensi.
Di sisi lain, saya lebih akrab dengan catper gaya non-fiksi naratif. Pernah baca artikel majalah atau salindia di medsos? Ya kayak gitulah.
Buku Wormser tampaknya menyajikan catper pendakian secara khusus. Maksudnya, kalau catper penjelajah lain biasanya gunungnya dibahas sedikit dan lebih banyak bahas daerahnya (karena emang laporan daerah). Karena topiknya lebih mengerucut ke pendakian itulah, saya jadi ingin baca bukunya.
Alasan lain adalah karena buku Wormser ini rupanya udah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Dari judulnya “Bergenweelde” menjadi “Kemewahan Gunung-Gunung.” Yesss, saya nggak perlu bolak-balik buka Google Translate untuk nerjemahin halaman satu per satu!
Sebagai catatan, kebanyakan catper penjelajah Hindia-Belanda (seenggaknya yang saya temukan online) mayoritas berbahasa Belanda. Atau kadang, Jerman. Nyari itu topik pakai keyword bahasa Indonesia atau bahasa Inggris sama nihilnya; hasilnya sama-sama sedikit. Beda dengan browsing pakai kata kunci bahasa Belanda atau Jerman. Padahal saya nggak bisa bahasa Belanda atau Jerman. :(
Karena buku Wormser sudah diterjemahkan, maka rasa penasaran semakin besar, haha.
Saya meluncur ke marketplace dengan harapan ada yang jual, meski second pun nggak apa. Duh, ternyata buku terjemahan '96 ini nggak banyak. Ada, sih, yang tulisannya masih tersedia. Tapi tokonya nggak terlihat meyakinkan. Dan berita buruknya, ini buku kayaknya udah nggak diterbitkan lagi.
Tiada harapan di pembelian, saya beralih ke peminjaman. Buku lawas begini biasanya tersedia di perpustakaan, khususnya perpus-perpus kampus. Saya menelusuri satu demi satu repository perpustakaan terdekat. Nihil. Hiks. Sebetulnya ada satu yang lokasinya cukup “terjangkau”, yaitu… Perpusat UGM. Rasanya pengin nggremeng ke diri sendiri, kenapa tahunya nggak dari dulu, waktu itu tempat masih berjarak sepelemparan batu dan sering disambangi setiap minggu. Hmm….
Untungnya, beberapa bulan kemudian, saya berkesempatan berkunjung ke Yogya. Saya udah ngerancang: mau ngehubungin adik kelas, minta tolong pinjamin itu buku dengan KTM-nya, lari ke rental buat fotokopi kilat, dan besoknya saya sudah memiliki kopian bukunya.
Namun rencana tinggal rencana. Waktu saya di Yogya ternyata amat mepet. Akhirnya saya ambil cara terakhir: nyari bukunya di perpus, baca, catat bagian yang dibutuhkan. Lagi-lagi, rencana ini pun tinggal rencana (LOL). Waktunya masih nggak cukup buat baca (astaga!). Akhirnya saya pun nggak jadi baca dan… menghabiskan satu jam lebih untuk memotret halaman satu sampai 350-an. Untuk dibaca kemudian di lain kesempatan. Alhamdulillah kamera ponsel sekarang sudah jernih, motret dokumen full satu halaman pun nggak jadi hambatan. Coba kalau ini kejadian saat kamera HP masih jadul. Itu huruf bisa ngeblur nggak kebaca semua :’)
[Awal Pencarian
Buku Pendakian Era Hindia Belanda]
Buat apa nyari catatan perjalanan/pendakian zaman dulu?
Sebenarnya saya nggak ada niatan. Waktu jadi anggota Pecinta Alam (PA), para anggota wajib survei dan cari tahu segala hal soal gunung yang akan didaki: medan, transpor, risiko, dsb. Minimal tahu jalur dan detail rutenya supaya nggak nyasar. Kalau sekarang, hal seperti ini bisa dicek di medsos atau website basecamp gunungnya. Namun, dulu medsos belum segencar sekarang. Cara buat cari tahu biasanya nanya teman/senior/organisasi PA lain yang udah pernah ke sana. Cara lain adalah baca-baca catatan perjalanan orang lain, umumnya di blog/website orang (ah jadi kangen zaman ketika blog/web dan mesin perambah masih diisi website yang organik, yang isinya beda-beda, bukan yang judul sedikit beda tapi isinya sama semua karena iklan-SEO-dsb). Cara lain adalah telepon basecamp, kalau mereka punya telepon.
Catper orang lain ini berguna banget buat mendaki, apalagi kalau gunungnya jarang didaki. Tanda-tanda yang pernah ditemui pendaki terdahulu bisa membantu banget buat kita menandai medan dan manajemen risiko. Kita juga jadi tahu kemungkinan apa yang bisa terjadi di pendakian kita, belajar dari pendakian orang lain.
Buat saya sendiri, rasanya seperti ada semacam “aha” moment ketika menemui hal-hal yang diceritakan dalam catatan orang lain. Hal-hal sederhana, sebenarnya. Tapi cukup buat saya dan teman-teman untuk nge-hype bareng.
“Wah, ini batu gede yang diceritain di catper!”
“Iya, ternyata gede banget seukuran kasur!”
“Kalau nemu batu ini, berarti kita udah di jalur yang benar.”
“Yesss, aku udah khawatir kita salah ambil jalan di percabangan tadi.”
Sama halnya seperti ketika membaca catatan seabad lalu, kemudian ngelihat wujudnya di depan mata.
Rasa penasaran itu kian meningkat saat mendengar cerita-cerita pendakian di tahun-tahun saat orang tua kita masih muda atau cerita dari senior tua. Dari cerita dan foto-foto mereka aja, pendakian dulu dan sekarang beda banget. Dulu lebih susah. Transpor minim dan harus lebih jauh jalan kaki, peralatan kemping nggak seringkas sekarang, dan jalurnya lebih liar. Saya jadi ngebayangin: zaman itu aja susah, gimana zaman penjelajah Hindia-Belanda? (Apalagi zaman nenek moyang di masa kerajaan-kerajaan dulu)
Membaca beberapa catatan, memang beda bangeeet. Antara lain:
- Sekarang, kita bisa bawa mobil/truk sampai desa terakhir. Satu moda transportasi cukup. Di abad itu, mereka harus gonta-ganti kendaraan: mobil, perahu, kuda. Paling sering pakai kuda.
- Sekarang, perbekalan bisa kita isi sekali jalan aja. Di era itu, mereka harus ngerencanain pit-stop untuk ganti kuda atau isi ulang perbekalan (pendakiannya lebih lama, berhari-hari)
- Di zaman kita (atau orang tua), kita bisa hiking dalam grup beberapa orang aja. Zaman itu, mereka hiking rombongan besar: ada penunjuk jalan, porter (bisa puluhan), juru masak, penerjemah, dsb.
Apa buku Wormser ini satu-satunya buku tentang pendakian?
Enggak. Sebenarnya, sebelum ‘berjodoh’ dengan buku Wormser, saya ketemu buku lain tentang pendakian gunung-gunung Indonesia karya Clement Steve, “Menyusuri Garis Bumi”. Tulisannya berlatar era 70-an. Ada juga buku “Manusia dan Gunung” tulisan Pepep D.W. dan “Zerowaste Adventure” karya Teh Siska Nirmala. Buku terakhir fokusnya bukan di catper macam medan dsb, tapi lebih ke manajemen perbekalan pendakian agar minim sampah. Selain itu apa lagi ya… mungkin ada yang tahu buku lainnya?

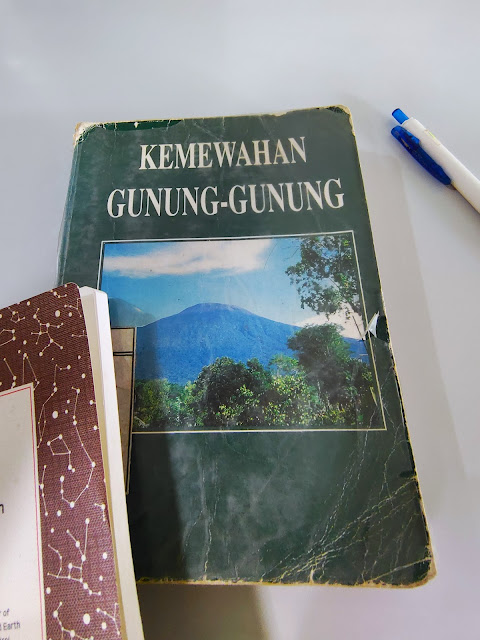

Tidak ada komentar: