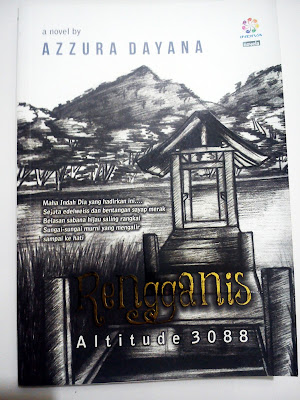Spontan. Cuma butuh waktu kurang dari sepuluh
detik untuk kami memutuskan rencana perjalanan ini. Saat itu, saya dan beberapa
teman lagi asyik ngadem sambil sibuk memelototi gadget masing-masing ketika
sebuah artikel jalan-jalan muncul di layar HP.
“Suroloyo itu mana ya?” tanya saya.
“Kulonprogo. Kenapa?”
“Enggak, ini muncul di artikel jalan-jalan.”
“Ke sana yuk?”
…
“Yuk.”
Akhir minggu itu juga, bersepuluh kami
berangkat ke puncak Suroloyo. Tempat ini merupakan salah satu puncak yang ada
di barisan Perbukitan Menoreh, kabupaten Kulonprogo, D. I. Yogyakarta. ‘Wah, ini kan bukit yang jadi judul komik Api
di Bukit Menoreh yang tersohor itu’, pikir saya. Makin semangat (dan
penasaran)lah saya. Apalagi dari review-review yang kami baca, tempat ini cocok buat ngejar sunrise. Beberapa malah menyebutkan kalau pemandangan siluet
Borobudur yang terlihat dari sini nggak kalah dengan pemandangan dari Puthuk
Setumbu. Tapi karena pada malas berangkat dini hari, kali ini mentari terbit
bukan jadi tujuan utama kami. 05.30 WIB kami ngumpul, pukul 06.05 kami
berangkat. Tak apalah, toh Borobudur tetap anggun dilihat meski bukan saat sunrise.
Kata Yuti, teman yang ngajak saya dengan
spontan sekaligus guide kami kali
ini, dari Jogja ke Suroloyo nggak makan waktu lama. Pagi itu, dengan kecepatan
rata-rata ± 50 km/jam, dalam 1 jam kami sudah sampai di lingkup wilayah perbukitan
Menoreh. Itu pun jalannya nyantai banget, banyak berhentinya, lagi. Entah isi
bensin, isi angin ban, jajan di minimarket (karena kami nggak sempat sarapan,
hiks). Kalau soal rute, wah maaf, saya
nggak tahu jalan persisnya. Tapi Yuti bilang, rute berangkat kami ini lewat
Samigaluh. Dari Seyegan, Sleman, lurus terus ke barat.
Selewat Sleman, Perbukitan Menoreh belum juga
kelihatan. Padahal normalnya sudah, kalau nggak ada kabut. Kawasan legendaris
ini baru terlihat jelas saat motor kami melintas di atas jembatan Kali Progo.
Garis-garis biru yang menandai Perbukitan
Menoreh mulai terlihat di kejauhan. Lapis-lapisnya dihiasi pepohonan yang
meranggas di sana-sini, menguning belum tersentuh hujan. Melongok ke bawah
jembatan, tampak Kali Progo yang meski menyisakan sedikit air, arusnya mengalir
tenang. Yuti bercerita bahwa ketika Merapi erupsi beberapa tahun lalu, sungai
inilah yang bertugas membawa material-material dari puncak gunung hingga
mengendap di Laut Selatan. Jadi nggak heran kenapa sungai ini lebar banget.
Bahkan dengan menyusutnya air dalam kondisi kemarau sekarang ini, alirannya
tetap lebar, meski kedalaman airnya di bawah lutut orang dewasa.
Kali Progo, foto diambil saat perjalanan pulang
Penduduk lokal mencari ikan di sungai yang kini dangkal
Saya kira di pelancongan kali ini, ini
satu-satunya pemandangan tepi jalan yang bisa bikin saya ternganga. Kenapa?
Kawasan yang kami tuju merupakan perbukitan batu. Saya sudah nyiapin hati
kalau-kalau nantinya pemandangan yang tersaji cuma bukit batu, gunung batu,
atau tebing batu yang tandus.
Perkiraan saya nggak salah, tapi kesimpulan itu
diambil terlalu cepat.
Pernah lihat, atau ingat, lukisan-lukisan
pemandangan yang suka ada di pameran? Itu, lukisan yang gambarnya hamparan
sawah yang luas. Di kanan-kirinya ada gubuk-gubuk petani kecil-kecil plus
pohon-pohon kelapa. Latar belakang gunung melengkapi kanvas. Pernah? Saya kira,
lukisan-lukisan itu cuma ada di imajinasi para pelukis yang saking pengennya
lihat pemandangan seperti itu saking nggak
ada, akhirnya menerjemahkan bayangannya pada karyanya.
Ternyata, lukisan seperti itu nyata ada. Di
depan mata.
Paket sawah komplet dengan pohon kelapa dan bukit.
Ini pemandangan yang sering saya lihat semenjak
kecil, di atas kanvas. Beranjak usia, saya nggak kunjung nemuin panorama
beneran yang seperti ini. Eh ternyata memang belum jodoh. Akhirnya dipertemukan
juga di perjalanan kali ini.
Selepas hamparan sawah, beberapa kilometer
jalan lurus kemudian, terdapat perempatan dengan pos polisi di sebelah
kanannya. Lurus, arahnya ke Samigaluh. Kanan, arahnya ke Sidoharjo. Keduanya
sama-sama bisa mengarah ke Suroloyo. Kami ambil lurus karena Yuti hanya pernah
lewat jalan lurus tersebut.
Jalan mulai menanjak memasuki perbukitan.
Persneling motor hanya berpindah-pindah antara nomor dua atau satu supaya kuat
melewati tanjakan demi tanjakan. Perumahan mulai jarang, meski toko-toko
kelontong tetap dijumpai di beberapa rumah pinggir jalan. Sekali-dua, tampak
galur sungai dengan batu-batu kalinya yang mendominasi di bawah jurang.
“Cuacanya mendung begini. Ntar di puncak,
kelihatan pemandangan di bawah nggak ya?”
Yup, cuaca mendung. Salah satu ‘musuh’ kalau
lagi bepergian, karena awan abu-abu itu bisa jadi isyarat turun hujan.
Gara-gara mendung inilah kami akhirnya putar haluan. Puncak Suroloyo yang
awalnya jadi tujuan pertama, jadi yang kedua. Rombongan memutuskan bahwa
perhentian pertama adalah perkebunan teh di kawasan yang sama.
Dua puluh menit kemudian, setelah tanjakan demi
tanjakan, sampai juga kami di perkebunan teh Nglinggo, Grojogan Watujonggol.
Perkebunan ini, selain untuk kebun contoh, juga dirancang untuk wisata. Objek
wisata ini dibentuk belum lama. Untuk masuk, kami cuma bayar Rp2.000,00 per
motor sebagai biaya parkir. Nggak ada tarikan retribusi lain.
Ini memang kebun teh, tapi jangan bayangkan
hamparan luas seperti foto-foto di National Geographic atau agrowisata kebun
teh Batu Malang. Karena kebun contoh, maka ukurannya pun relatif lebih kecil
sehingga hamparannya pun nggak terlalu luas. Belum lagi karena dikelilingi
perbukitan batu, pandangan pun terasa kurang lapang.
Tapi, itu bukan berarti perjalanan kami kemari
nggak worth it. Hamparan hijau teh
yang menyegarkan, apalagi saat itu masih sepi, sangat-sangat mampu jadi pelepas
penat. Terpikat histeria, kami berlarian ke sela-sela rimbun teh yang setinggi
pinggang. Cuaca yang berubah cerah, cuma meninggalkan gerumbulan awan-awan
kecil penghias langit biru terang. Angin sejuk semilir meniup pucuk-pucuk teh,
menggoyangkan beberapa dahan-dahan kurus pepohonan wind barrier. Kelompok burung dan rombongan capung hilir-mudik
terbang dari satu area ke area lain.
Teras-teras perkebunan teh
Hijau segar
Hutan pinus di bukit seberang
Burung dan kumpulan capung melintas tanpa aba-aba di depan mata
Bayangan gunung di kejauhan
Menurut saya, waktu paling cocok berkunjung ke
kebun teh memang waktu pagi. Langit sudah terang, tapi tak cukup terik untuk
memaksa kita memakai topi. Semakin pagi pula, semakin sejuk hawa yang didapat,
dan semakin sepi pula hingga kita bebas berlarian kesana-kemari tanpa perlu
malu dilihat pengunjung lain.
Pukul sembilan lebih, kami baru rela pergi.
Saatnya bertolak ke Suroloyo.
Arah ke Suroloyo berarti kami harus balik kucing dulu. Di suatu pertigaan
yang sebelumnya sudah kami lewati (alert:
pertigaan ini jangan dijadikan pedoman karena ada banyak pertigaan), kami ambil
arah ke kiri. Nggak perlu takut nyasar karena ada papan petunjuk arah.
Percabangan jalan pun nggak terlalu banyak.
Kalau tadi persneling bisa gonta-ganti di nomor
satu atau dua, maka kali ini nomor satu yang mayoritas dipakai. Jalan yang
nanjaknya hingga 45 derajat, plus belokan yang suka muncul nggak kira-kira,
bikin pengendara harus ekstra hati-hati kalau nggak mau nyasar ke jurang di
tepi. Di jalur ini, kami sering menemui tanjakan, lalu belokan tajam yang
nanjaknya juga nggak kira-kira. Mirip-mirip jalanan di Cangar, Batu Malang.
Kalau nggak PD atau skill motornya
belum mumpuni, mending disetiri teman lain yang PD dan mumpuni.
Di sepanjang jalan, selain pohon jati, sering
ditemui pohon kakao atau pohon kopi. Ternyata, warga lokal juga produksi kopi
Arabika. Di parkiran bawah Suroloyo, ada satu warung kopi Arabika.
kiri: buah kopi, kanan: bunga kopi
Kami sampai di parkiran kira-kira pukul sepuluh.
Sebelumnya ada pos penjagaan untuk bayar tiket masuk. Motor dikenai biaya
Rp1.000,00 dan per orang Rp3.000,00. Di parkiran, ada biaya parkir berkisar
Rp1.000,00-Rp2.000,00, saya lupa.
Ternyata, ada tiga puncak di daerah ini. Dari
satu puncak ke puncak lain lokasinya cukup dekat, tapi harus pakai motor karena
dempor juga kalau jalan kaki naik-turun tanjakan. Karena nggak punya niat
menjelajah, kami cukupkan naik ke Suroloyo aja. Suroloyo merupakan salah satu
puncak paling terkenal, kemungkinan karena Sultan Agung Mataram dulu menerima
petunjuk gaib di sini. Mungkin juga karena ini puncak tertinggi Perbukitan
Menoreh.
Ada 286 anak tangga hingga ke puncak. Entahlah,
saya nggak berniat ngecek karena napas pun sudah satu-satu mendaki anak tangga.
Bukan berarti perjalanan naik ke atas sangat berat. Kalau niat, 5-10 menit juga
sudah sampai. Tapi ini tangga, yang artinya jarak langkah kaki kita diatur
tangga. Ukuran tangganya pun tak sama.
Napas yang diambil satu-satu mengantar kami ke
suatu tanah lapang yang tak terlalu luas, titik tertinggi Perbukitan Menoreh,
1.019 mdpl. Ada satu bangunan kecil di satu pojok. Bau kemenyan menguar dari
patung dewa di sudut bangunan itu. Kelopak-kelopak mawar bertebaran, sisa-sisa
doa pengunjung.
Rangkaian Perbukitan Menoreh berkilo-kilometer
jauhnya tampak seperti rantai. Antarbukit berbatas warna biru yang
berbeda-beda. Jauh di bawah, perumahan, pedesaan, bahkan lurus jalan terlihat
jelas. Bisa dibayangkan saat malam tiba, kerlap-kerlip lampu bakal jadi
pemandangan yang wah.
Gradasi warna gugusan Perbukitan Menoreh
Gunung Merapi, Sindara, Sumbing, ataupun
Merbabu memang tak terlihat karena tertutup kabut. Pun siluet Candi Borobudur. Tapi cukuplah
rangkaian Menoreh jadi penghapus kecewa. Seenggaknya, kami jadi tahu wujud
nyata setting serial komik legendaris Indonesia karya S.H. Mintardja itu, Api
di Bukit Menoreh.